Guys….
Buat kamu yang ada di Perancis dan sekitarnya. Jika kalian ada waktu tanggal 14,15,16 September ini mampir ya Guys ke stand Reseau Indonesia di acara akbar Fetr de l himanite, cekidot guys…
Komikku dipamerin di sini. See u at Paris, guys!
Guys….
Buat kamu yang ada di Perancis dan sekitarnya. Jika kalian ada waktu tanggal 14,15,16 September ini mampir ya Guys ke stand Reseau Indonesia di acara akbar Fetr de l himanite, cekidot guys…
Komikku dipamerin di sini. See u at Paris, guys!
Catatan Catatan Yang Tertinggal Dari Film Dokumenter (3)
Guys…Di Busan Internasional Film Festival 2014 saya diundang menghadiri acara penting. Malam itu beberapa filmmaker mendapatkan anugerah award. Satu di antaranya Joshua Oppenheimer sutradara asal Denmark yang filmnya mungkin kalian udah tahu ya, itu tuuuh “The Act of Killing” (TAoK) dan “The Look of Silence”(TLoS).
Malam itu guys kalok gak salah tanggal 10 Oktober 2014, Joshua dapat Busan Cinephile Award for best documentary, itu penghargaan bergengsi guys, ampe ngiler liatnya hahahaa cesss…cesss…
Tapi di catatan ini guys, bukan penghargaannya yang ingin saya bahas, tapi filmnya. Apa sih yang menarik? Gini guys, tahu gak perihal peristiwa 65? Itu Guys yang tiap bulan September tanggal 30 dari sejak jaman Orde Baru sampe jaman pemerintahan era milenia ini diperingati sebagai hari pemberontakan PKI? Kemudian tanggal 1 Oktobernya jadi hari Kesaktian Pancasila?
Nah, guys sebagai generasi milenia kita kayaknya penting deh tahu sejarah peristiwa 65 itu. Kalau kita riset guys, banyak banget catatan sejarah yang simpang siur perihal siapa yang berontak dan siapa yang menunggangi peristiwa yang mengakibatkan ratusan ribu anggota dan simpatisan PKI (Partai Komunis Indonesia) dibantai akibat perang saudara sesama orang Indonesia waktu itu.
Tapi guys, saya ga mau bahas soal itu yaaa… maklum guys itu sejarah sensitif, kagak enak dibahasnya. Trus bahas apa dong oppaaaaa? Hahaa begitu tuh kalok terpengaruh sama budaya popnya Korea, nanya nya pake Oppaaa… ayomg haseo Opaaaa… xoxoxoxxoxoxo
Okey guys, kita mulai dari pertanyaan bagaimana ceritanya si sutradara Joshua Oppenheimer bisa menemukan sosok Adi Rukun dan menjadi karakter utama di filmnya, bagaimana awalnya Joshua bisa meletakkan tokoh Pemuda Pancasila di Sumatra Utara yang disegani fidunia wal akherat (hehe di akherat disegani apa tidak gak tahu ya guys) bernama Anwar Kongo ke dalam filmnya?
Kalau kita dapat jawaban dari dua pertanyaan itu, guys maka insya Allah kita bisa mulai tahu nih bagaimana film yang ceritanya kuat kayak TaOK dan TLoS bisa dibikin. Saya menyebutnya bukan hanya dokumenter guys, tapi Cinematic Documentary… hehe keren ya guys rasanya dengar istilah itu kemrenyes gimana gituuhh batin ini seolah olah…weww
Begini guys, 1965 adalah peristiwa besar guys, ada melibatkan banyak tokoh, organisasi, peristiwa, kepentingan dari luar negeri dan macam-macam deh, very complicated sampai-sampai CIA (Dinas Intelejen Amerika) membuka data 30 tahun kemudian bahwa mereka terlibat dalam urusan 65 di Indonesia. Tuh kaaaan rumit kaaan guys…ngeriii boooo…
Dari kompleksitas kisah-kisah 65 itu guys, seorang filmmaker dituntut untuk mengambil cerita yang paling keren, menarik dan enak dilihat. Yaaaah tahu sendiri ya, film-film seputar 65 baik fiksi maupun dokumenter biasanya berdarah darah ekstra kesedihan guys… bikin takut aja kalok pas kencing sendirian di belakang rumah hahahaa.
Di sinilah kecerdasan seorang Joshua Oppenheimer diuji guys, dia ngga kejebak ke bentuk profil seorang Anwar Kongo atau Adi Rukun pada dua film yang berbeda itu. Joshua berhasil menemukan inti sari semua kompleksitas peristiwa menjadi sederhana. Dari aktifitas tukang jual kacamata Josua memulai bercerita untuk “The Look of Silence”. Hasilnya keren guys. Kacamata, peralatan periksa mata, dan berbagai aktifitas Adi Rukun sebagai penjual kacamata bisa menjadi semacam simbol bagaimana bangsa ini melihat persoalan 65 dalam keseharian setelah peristiwa itu lama berlalu, peristiwa yang meninggalkan trauma, meninggalkan jejak pilu bagi anggota keluarga, baik pelaku maupun korbannya. Tuh guys mulai terlihat gak apa yang mau saya bahas di catatan ini?
Anwar Kongo sebagai sosok yang ditakuti, dia terobsesi oleh lakon-lakon Hollywood. Widiiihhh cadas kan? Semacam Iblis berhati Rinto ( penyanyi dengan lagu lagu melankolis di tahun 80-90 an). Joshua memang tidak gamblang mengungkap fakta bahwa CIA terlibat dalam peristiwa 65 di Indonesia yang mengakibatkan suksesi Jendral Soeharto menjadi presiden menggantikan Soekarno.
Obsesi Anwar Kongo sebagai aktor film, dan kecintaannya pada film-film Hollywood, terinspirasi Al Pacino dll itu semacam simbol bahwa Amerika mainded sudah ada di kepala orang Indonesia sebagai “Hero” secara visual…. guys berat yaaak? Nggak juga sih guys… ini kayak coca cola campur kebab sebenarnya… hahaha bikin kenyang otak..
Woiiiii apa hubungannya dengan buah sama sari buah?
Eeeh… iya guys, ckckckckcck jadi ngelantur ya. Okey guys begini… catatan di atas guys membuat kita tahu bahwa benda, peristiwa, suasana psikologis ternyata bisa menjadi perantara bercerita yang menarik. Jadi… nggak perlu wawancara kayak di film Banda the Dark of Forgotten Trail itu wawancara melulu… hehehe di Wikipedia juga banyak… anak kemarin sore yang baru ikutan workshop film juga bisa tuh bikin begituan… ups nggak juga kelessss…
Jadi guys, supaya kita nggak bikin film yang kayak Banda itu, yang isinya udah ada di wikipedia dan gambar-gambar cantiknya juga sebelumnya dah banyak orang upload di Instagram. Supaya kita cerdas dikit yaaa bikin film yang ngga pernah dibahas di sosmed maupun susah dicari materinya di Wikipedia… itulah guys yang dinamakan sari buah nya cerita.
Tentu ini butuh riset mendalam guys, dananya juga ga sedikit, tapi yang lebih penting adalah seorang cinematic documentary filmmaker harus peka dan banyak membaca sehingga dia bisa memahami suatu peristiwa dan mengambil intisari dari peristiwa itu, dengan berangkat dari peristiwa atau benda yang kecil namun kemudian bisa membawa kepada cerita yang besar.
Joshua Oppenheimer ga perlu datang ke Museum Loebang Boeaya deket Asrama Haji Pondok Gede sana untuk menceritakan peristiwa 65, dia tidak perlu wawancara Jendral Soeharto ( orangnya dah gak ada) untuk mengklarifikasi ada dan tidaknya pembantaian anggota PKI atas perintahnya sebagai pangkopkamtib berbekal Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) waktu itu.
Dalam bertutur, Joshua membutuhkan sosok yang tak pernah dikenal dalam catatan sejarah Indonesia, seorang anak lelaki yang tumbuh dalam suasana traumatik akibat peristiwa 65 karena anggoa keluarganya dibantai orang orang yang memiliki kedekatan dengan keluarganya. Atau Anwar Kongo yang suka bercerita secara detail
Tentang bagaimana ia membantai setiap korbannya dengan bernyanyi, bersiul dan menari-nari.
Dua karakter yang luput dari catatan besar dalam sejarah perjalanan Republik Indonesia itu ternyata jadi karakter yang sangat kuat, menjadi jembatan naratif dalam film dokumenter, dan Joshua dengan kecerdasannya mampu memungutnya dari tumpukan rongsokan sejarah yang hanpir terlupkan dan memolesnya menjadi catatan visual yang tentunya kadi keren dalam bentuk film.
Guys… layak ya film kayak gitu masuk nominasi Oscar? Xixixiixii…
Jadi Guys, ketika semua cerita besar saat mau diwujudkan harus menggunakan budget besar, kita harus sadar ya bukan anaknya kongklomerat yang kaya raya sehingga gampang dapat duit untuk bikin film, atau pinter bikin proposal film budget gede, kita berangkat dari diri sendiri aja dulu, bagaimana dari kolongmelarat ini guys kita mulai setia meneliti hal hal kecil, karena dari situ kita bisa berangkat untuk menceritakan hal-hal besar.
Misalkan; Panglima Besar Jendral Soedirman, kita bisa memulai membuat film dengan cerita kecil ketika seseorang memberikannya jas panjang yang sampai hari ini menjadi sangat fenomenal. hayooooo… Siapa yang tahu cerita darimana jas panjangnya Jendral Soedirman berasal? Gak ada yang tahu kaaan?
Misalkan, cerita tentang Lagu Indonesia Raya, berangkat dari kisah WR. Supratman mencari satu lembar catatan not balik yang hilang waktu dia menciptakan dan mangaransemen lagu itu, atau bagaimana menjelang malam 28 Oktober itu, WR Supratman sibuk mencari toko penjual senar biola karena satu senarnya putus, sementara besok sudah terjadi momentum Sumpah Pemuda.
Misalkan; Cerita tentang Kyai Ahmad Dahlan, berangkat dari cerita perpustakaan yang ia bangun sebagai tempat interaksi dan pengajaran kepada murid-muridnya. Guys… nih cerita aja ya, bayangkan guys, film tokoh tokoh p legendaris Indonesia di film film Indonesia jarang yang ada adegan membaca buku, atau mendiskusikan isi buku, guys! Padahal mereka itu tokoh yang makan buku hahaha
Artinya apa tuh? Artinya filmmaker selalu membuat film berdasarkan gelondongan buahnya, bukan melakukan riset mendalam untuk menemukan sari buahnya… ah masaaaak? Xixixiixi beneran guys!
Jadi gitu guys curcol saya perihal memilih menceritakan buah atau menceritakan sari buahnya… semoga catatan ini berdaya guna ya guys… jolali share kalau merasakan manfaatnya yaaa…
Selamat berpikir ya guys… moga moga bisa sampai kepada permukaan bulan kayak Neil Amstrong, atau minimal melayang layanglah di luar angkasa kayak Yuri Gagarin… jangan lupa menginjak bumi guys, kameranya masih di tripod! Hahahahahaa
Guys, soal pendidikan film ya, aku kok pengen kalian merasakan kayak Neil Amstrong pertama kali nginjal kakinya di Bulan. Persetan itu fiksi atau dokumenter!
Semoga ini bukan atatan yang berbahaya…. Xoxoxoxoxoxoxo
Catatan-catatan film dokumenter yang tertinggal (2)
Guys…
Kalok kalian suka nonton film di bioskop 21 atau XXI tentu kalian akrab sama film Hollywood ya… simpelnya orang bilang itu film fiksi.
Ya, fiksi guys, buat anak anak sekolah film IKJ, bahasa film akademiknya agak keren sih film naratif. Nah guys, film naratif itu biasanya berangkat dari imajinasi. Makanya seringkali kita lihat tokoh dan cerita di dalamnya itu khayalan belaka. Namanya juga fiksi hehehe.
Di catatan sebelumnya saya sudah pernah singgung tuh, perkembangan teknologi membawa dampak pada perkembangan bentuk dan gaya bertutur dalam film. Kalok dulu kameramen National Geographic harus bawa kamera dan banyak ken-ken seluloid, budget produksi harus ditekan sehingga merekam realitas hanya 10 detik per shot. Gaya TVRI guys…katanya begitu.
Ini saya mau cerita guys, pengalaman kembara ke Jepang tahun 2011 dan 2012. Nah, di tahun 2012 itu guys… saya diundang ke acara besar di bulan Oktober ya, nama acaranya Tokyo Documentary Dream Show. Ada film menarik yang bikin saya penasaran bener.
Judulnya “Three Rooms of Melancholia” sutradaranya bernama Pirjo Honskasalo asal dari Finlandia. Tahu ga guys? Saya tonkrongin film panjang itu sampe tuntas tas tas di kredit titel terakhir. Trus waktu penonton pada pergi, saya masih terpaku di bangku sinema! Kenapa terpaku? Ya bukan karena encok atau lemes guys, tapi beneran waktu itu saya gegar guys, kepala saya cetar membahana… dalam benak saya bertanya, ” Ini film dokumenter apa fiksi?”.
Syukur alhamdulillah ya guys, saya segera menyadari kalok itu even film dokumenter. Lalu saya ga bisa tidur guys, bukan karena lapar di negara orang… tapi sebagai filmmaker saya berpikir, bagaimana si filmmakernya mas Pirjo itu bisa bikin film kayak gitu? Apa isi bagasi kepalanya ya? Bagaimana pengalaman hidupnya? Apa aja bacaan bukunya? Siapa orang orang yang mendukungnya mewujudkan film semacam itu?
Edan! Film itu menggoyahkan isi kepala saya guys, dokumenter kok gak ada wawancaranya dan sangat naratif, kayak fiksi di film-film bioskop 21! Nah, guys… sejak saat itu saya terus mengembara mencari dan mencari, belajar dan belajar menemukan jawaban dari pertanyaan, “Apa batasan film dokumenter?
Waktu kuliah di Fakultas Film dan Televisi (FFTV) Institut Kesenian Jakarta (IKJ) di hari-hari pertama kuliah, dosen kami memperkenalkan berbagai film yang tercatat sebagai tonggak sejarah sinema dunia, guys. Tiap hari guys, mata dan otak saya digempur sama tayangan yang terasa aneh waktu itu. Ada film yang masih hitam putih, ada juga yang berwarna. Ada yang lamaaaaaaaaaaaa banget guys, sampai sampai kalok nonton bisa tidur, bangun, tidur lagi… pas bangun belum juga kelar tuh film. Ada film berjudul Sleep, tahun 1963 karyanya Andy Warhol guys! Gilak tuh film beneran bikin tidur hahaha…
Satu di antara film itu sampe hari ini masih terpatri di kamus kesadaran saya guys, filmnya orang Amerika namanya Robert J Flaherty berjudul “Nanook of The North”. Itu kan film yang dibikin tahun 1920 an sekian ya, saya nonton tahun 1998. Mbayangin kameranya segede apa, trus gimana menyesuaikan dengan cuaca dan iklim di kutub utara sana, trus berapa rombongan sirkus yang terlibat di film itu. Berapa biayanya, coba dihitung. Bah! Ribet banget guys…! Lalu kenapa masih mau bikin film dokumenter ya? Itulah guys, namanya juga cinta! Kalok dah cinta, taik kucingpun dimakan rasa cokelat bukan? Xixixixixi…
Guys, para kritikus bilang film kayak “Nanook of the North” atau “Three Rooms of Melancholia” itu masuk dalam golongan film dokumenter observatory. Nggak tahu deh kok sampe dimasukin ke golongan begituan. Mungkin karena dibikinnya tuh pake sabar kalik ya? Sebab film kayak begituan hanya bisa dikerjakan jika si filmmaker nongkrongin tuh si subyek atau karakter yang ada di film itu. Observasi guys!
Anyway… balik ke pertanyaan dokumenter apa fiksi? Nah guys akhirnya nih saya jadi berkelana deh nyari jawabannya. Akhirnya guys, menurut pengalaman pencarian itu, saya bisa menarik kesimpulan begini. Fiksi dan dokumenter hanya dibedakan dalam dua prinsip dasar. Fiksi berangkat dari imajinasi, sementara dokumenter berangkat dari realitas, fakta dan data. Filmmaker dengan pendekatan fiksi mewujudkan imajinasinya menjadi realitas sinematik, sedangkan filmmaker dengan pendekatan dokumenter menjemput realitas menjadi realitas sinematik…. halaaah sok mendalam ya saya guys?
Ini contoh ya guys, semisal begini;
Cerita tentang Suku Wana yang mendiami wilayah adat Hutan Morowali Sulawesi Tengah. Waktu itu ada kerjaan dari Tifa Foundation dan Interseksi Foundation tahun 2008. Mau bikin film dokumenter tentang hak minoritas Suku Wana sebagai bagian dari Indonesia. Selama satu bulan guys, saya berada di hutan rimba belantara jauh dari es cendol, nggak ada internet, ngecharge batere kamera harus menggotong generator ke mana mana. Maklum guys, suku Wana itu nomaden, peladang berpindah. Metode observasi berlaku selama satu bulan itu. Akhirnya saya jadi filmmaker dokumenter nomaden juga deh… asem..
Saya menggunakan wawancara untuk merajut cerita-cerita dari orang-orang di Kajupoli dan Marisa ( frontier ekonomi mereka yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten, port Kolonedale). Saya juga menggunakan perekaman mengikuti setiap kegiatan mereka. Kesulitannya nih di lapangan, mereka sering pakai bahasa Wana, guys kalau pas saya rekam. Sementara budget ga ada buat bawa mereka ke Jakarta buat terjemahin. Nah, dari wawancara itu akhirnya saya mendapatkan data bagaimana mereka memasuki kehidupan modern namun masih memiliki semangat untuk mempertahankan adat istiadat sebagai kesatuan adat dan wilayah orang Wana.
Guys, kalau kalian jadi orang Wana, bisa bayangin guys bagaimana menyesuaikan diri menjadi Indonesia? Bagaimana mereka memutuskan memilih agama, memilih wilayah tempat tinggal karena wilayah mereka terpatok kebijakan Taman Nasional misalnya? Memilih cultural heritage atau hidup bebas menyesuaikan diri dengan perubahan?
Kemudian bagaimana mereka menyamakan nilai kebutuhan ekonomi dari barter ( tukar menukar ) menjadi jual beli dengan uang? Lalu bagaimana mereka harus mengikuti sistem demokrasi melalui pemilihan umum, siapa yang mereka pilih? Apakah mereka terwakili hak politiknya sebagai minoritas? Hmmmm… gak gampang banget nyatanya.
Saya meminjam realitas mereka dengan rekonstruksi. Dengan demikian batasannya adalah tidak melebihi dari fakta yang ada. Semisal rekonstruksi upacara Mamago, upacara yang dilakukan untuk berkomunikasi dengan roh-roh leluhur. Salah satunya menggunakan sarana air Pongase (minuman beralkohol asli Wana).
Dari rekonstruksi itu kita mendapatkan data audio visual yang mendekati realitasnya. Mendekati ya guys, karena kalau tidak direkonstruksi maka filmmaker harus menunggu bisa berbulan-bulan sampai mereka melaksanakan upacara adat itu sesuai almanak atau kalender adat mereka.
Apakah kemudian itu disebut fiksi? Karena menempatkan kamera, angle dan komposisi berdasarkan kemauan si filmmaker?
Apakah itu disebut dokumenter karena menggunakan fakta yang ada di lapangan dan hanya meminjam realitas dari fakta yang ada?
Guys, kita bisa menuntaskan catatan-catatan yang tertinggal dari pembuatan film dokumenter ini dengan jalan diskusi. Silahkan guys kalau mau bertanya di sini. Tentunya lihat dulu guys filmnya, ada kok di youtube… mau saya bagi linknya? Nihhh guys cekidot!
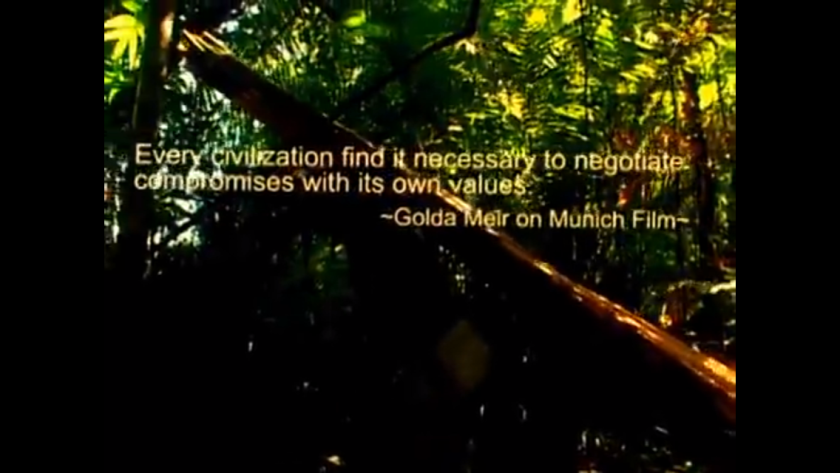
Ada empat bagian ya guys… silahkan dilihat, kalau suka ya tolong dilike, jangan lupa guys klik juga subscribe nya yaaa maklum guys, saya masih fakir subscribe hehehe…
Thanks ya guys udah meluangkan waktu baca curcolku perihal film dokumenter… ditunggu yaaaa responnya… kritik? Boleh guys kritik aja, yang pedes sekalian! Hahaha… semoga berguna, salam!
(Prolog gaya Gen Milenia)
Menggeluti film dokumenter adalah pilihan. Akan tetapi menguliti film dokumenter selama hampir 19 tahun sejak pertama masuk kuliah film di Fakultas Film dan Televisi (FFTV IKJ) Institut Kesenian Jakarta (IKJ) bisa jadi bukan lagi pilihan akan tetapi merupakan suatu ketidakwarasan. Ya tidak waras karena cinta yang terlalu mendalam… eaaaaaaaaaaaaa 😀
Manfaat yang lain masih banyak lagi, misalkan catatan nomer telepon kenalan bertambah, pengenalan adat istiadat dan kebiasaan orang lain bertambah, catatan harian berjibun, kemampuan teknis semakin tajam, skill semakin matang, apa lagi? Tentu banyak. Yang tidak bertambah barangkali adalah penghasilan, guys! Hahahahaa ini penyataan jujur sihh guys.
Tapi tenang yaaaa guys, pagu produksi film dokumenter yang murah itu sudah gugur di tahun 2017 dengan lahirnya film Banda, The Dark Forgotten Trail yang disutradarai seniman ternama dari Indonesia, mas Jay Subiyakto dan dikawal oleh punggawa produser mas Abduh Azis dan mbak Lala Timothi. Para pegiat film dokumenter Indonesia layak bergembira, dan semoga semakin giat berdoa yaaaa… agar pagu itu tetap stabil, bisa makin naik tapi jangan turun. Hahaha… guys, kalok setiap film dokumenter diproduksi dengan budget milyaran, aku kok yakin ya filmmaker dokumenter bakalan sejahtera. Tentunya harus ada industrinya, guys, di dalamnya ada sistem yang mengatur penyehatan dana film, distribusi dan eksibisinya…. ho oh… bener kalok kata mbak Kim Hyonf Suk direktur Asian Documentary Network yang tiap tahun nongkrong di Festival film Busan Korea Selatan. Hihihi…
Nahhh guys, dari situ tuhhh saya merasakan perkembangan teknologi digital berandil besar dalam mengembangkan cara bertutur di dalam tradisi pembuatan film dokumenter. Jika dulu dengan media pita seluloid dan pita suara seorang filmmaker dokumenter hanya bisa merekam dalam durasi pendek, lantas harus mengikuti proses laboratorium yang penuh prosedur, maka film tidak bisa dibilang murah hingga rilis sebagai media pandang dengar.
Kayak dukun harus topo broto belasan tahun menahan haus lapar untuk mendapatkan kesaktian mandraguna, otot kawat tulang besi, seorang filmmaker harus membekali ilmu film dari sekolah film selama bertahun-tahun, guys! Sampai lumutan…hahaha
Kalau sukak sama tulisan-tulisan saya ojo lali yooo, Jangan lupa share, like, atau tanggapin yaaaa…
Semoga catatan ini menarik buatmu para pembaca semuanya, Guys.
Terimakasih… Tabik!
Salam hangat
Daniel Rudi Haryanto
– Alumni FFTV IKJ 2005
– Peraih anugrah Director Guild of Japan Award, Yamagata Int’l Documentary Film Festival 2011
– Peraih Special Jury Mention dari Cinemasia Amsterdam 2014,
– Alumni Dare to Dream Asia 2015
– Alumni American Film Showcase 2016, Southern California University ( Amerika Serikat )
– Supervisor di Eagle Award Documentary Competition 2015,2016,2017
– Pendiri Cinema Society, Indonesian Gilm Watch, Sukarelawan di Minikino, Bali.
– Pendiri Studio dan Laboratorium Visual Sarang Berangberang, Indonesian Documentary Engine.
Pembunuhan atau pembantaian terhadap umat manusia, apapun agamanya, ideologinya, adalah suatu tindakan yang keji dan melanggar kemanusiaan.
Konflik dan pelanggaran hak asas manusia di Rohingya membuka mata dunia akan semakin melemahnya kesadaran umat manusia terhadap kemanusiaan.
Pembantaian umat manusia itu membawa dampak besar di Asia. Terutama di Indonesia. Solidaritas dan keprihatinan muncul sebagai wujud kesamaan sebagai manusia.
Rohingya menjadi jendela yang membuka mata manusia bahwasanya potensi pelanggaran terhadap kemanusiaan itu ada di sekitar kita.
Selain Rohingya, banyak wilayah di Indonesia mengalami kesamaan potensi pelanggaran kemanusiaan.
Tanah-tanah ulayat di Papua, Borneo, Sumatra, Jawa, Sulawesi, dan wilayah lain di Indonesia akibat agresivitas pemilik modal dan oknum aparat negara menjadi potensi besar konflik yang bakal berkepanjangan.
Genocida tidak hanya berupa pembunuhan atau pembersihan etnis belaka, namun genocida telah dimulai sejak hasrat memiliki dan menguasai bercokol di hati manusia.
Rohingya penting untuk dibahas, umat manusia yang tertindas harus dibela, begitu juga mereka yang ada di Papua, Atjeh, Sumatra, Jawa, Sulawesi, Borneo dan wilayah lainnya.
Mereka belum tentu seagama atau seideologi denganmu. Akan tetapi kitah manusia adalah sama. 
Komik ini saya buat sebagai bentuk solidaritas kepada umat manusia yang tertindas di Rohingya dan di seluruh muka bumi.